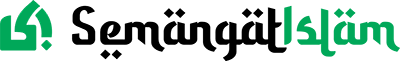Oleh: Burhanuddin Muhtadi
Dosen UIN Jakarta dan Direktur Eksekutif Indikator Politik
Saya mengenal pertama kali nama Azyumardi Azra ketika pada tahun 1995 membaca tulisan-tulisannya yang bertebaran di Jurnal Ulumul Qur’an. Kebetulan saat itu saya masih “nyantri” di Madrasah Aliyah Negeri Khusus (MAPK) Surakarta.
Seorang kakak kelas menjajakan jurnal Ulumul Qur’an, baik edisi baru atau lama, di kamarnya. Dan saya lebih sering menikmatinya secara gratisan ketimbang membelinya. Pada saat itulah saya terkesima dengan produktivitas Azra tanpa sepenuhnya memahami pemikiran-pemikirannnya yang disampaikan dengan untaian kalimat dan diksi yang berat untuk seorang anak Aliyah seperti saya.
Di antara tokoh-tokoh pembaharu Islam yang buku-bukunya saya baca semasa di MAPK Surakarta, Azra memang lebih “junior.” Jika Nurcholish Madjid sudah dikenal dengan pemikiran desakralisasi Islamnya, Harun Nasution dengan teologi rasionalnya, Munawir Sjadzali dengan reaktulisasi Islamnya, Muslim Abdurrahman dengan teologi transformatifnya, nama Azyumardi Azra dan pemikirannya pada saat itu belumlah menjadi “household name.”
Saat itu belum banyak yang mengenal disertasi Azra di Columbia University yang bertajuk “The Transmission of Islamic Reformism to Indonesia: Network of Middle Eastern and Malay-Indonesian Ulama in the Seventeenth and Eighteenth Centuries.”
Buku terjemahan disertasinya yang diterbitkan Mizan dengan judul yang menohok “Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII” baru meledak setelah saya berlabuh di Ciputat pada 1996.
Munculnya nama Azyumardi Azra dalam daftar intelektual Muslim pada medio 1990-an membuat reputasi IAIN (UIN) Jakarta makin mengkilap. Meski orang tua menyarankan saya kuliah di IAIN Yogyakarta karena pertimbangan biaya, saya bersikeras melanjutkan sekolah ke IAIN Jakarta karena pesona para cendekiawan Muslim yang umumnya bermarkas di Ciputat.
Ketika saya menginjakkan kaki di IAIN Jakarta, Azra baru saja menyelesaikan program post-doctoral di Oxford University. Karier keilmuannya yang mengagumkan membuat Rektor IAIN pada saat itu, Prof Dr Quraish Shihab, mendapuk Azra sebagai Pembantu Rektor Bidang Akademik.
Terpilihnya Quraish Shihab sebagai Menteri Agama pada 1998 membawa keberuntungan tersendiri bagi Azra. Ia naik kelas menjadi Rektor IAIN Jakarta di masa-masa genting jelang berakhirnya kekuasaan rezim Orde Baru.
Sebagai mahasiswa yang turut berdemonstrasi bersama ribuan mahasiswa IAIN, saya sering melihat Azra “melepas” keberangkatan “pasukan” mahasiswa ke Gedung DPR RI. Setelah Soeharto jatuh, Azra makin dekat dengan aktivis mahasiswa. Sebagai Rektor ia sangat akomodatif terhadap tuntutan mahasiswa membubarkan sistem senat mahasiswa yang dianggap bagian dari warisan Orde Baru menjadi Badan Eksekutif Mahasiswa yang lebih otonom.
Keakrabannya dengan dunia aktivisme sebenarnya tidak mengherankan karena Azra sendiri datang dari kalangan aktivis pada masanya. Ia adalah mantan Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Jakarta (1979-1982) dan Ketua Umum HMI Cabang Ciputat (1981-1982).
Pada saat TB Ace Hasan Syadzili terpilih sebagai Presiden BEM yang pertama (1999-2000), saya ditunjuk sebagai Menteri Bidang Penelitian dan Pengembangan Intelektual.
Akibatnya saya sering menemani TB Ace beraudiensi dengan pihak rektorat. Kedekatan saya dengan Azra makin intensif ketika saya terpilih dalam pemilu raya sebagai Presiden BEM periode 2000-2001. Pada saat itu Azra sedang sibuk-sibuknya melakukan transformasi IAIN ke UIN Jakarta.
Dalam beberapa kesempatan saya diajak Azra bertemu dengan banyak pihak dari kalangan pemerintahan atau lembaga asing untuk menjelaskan mimpi besarnya mengubah IAIN ke UIN. Jurusan dan fakultas umum ia buka, termasuk Fakultas Kedokteran, Sains dan Teknologi, dan lain-lain. Azra suatu ketika berkata, “Melalui transformasi dari IAIN ke UIN, anak-anak pesantren bisa bermimpi menjadi dokter atau insinyur.
Jika tidak ada UIN, mereka akan tarung bebas ke kampus-kampus umum dengan anak-anak SMA. Ini jelas tidak fair. Anak-anak pesantren perlu affirmative action.”
Keberhasilan Azra menyulap IAIN menjadi UIN Jakarta membuat banyak pihak berdecak kagum. Kampus IAIN yang dulu relatif kumuh ia sihir jadi mengkilat. Entah berapa dana yang berhasil Azra galang untuk mewujudkan mimpi mengkonversi IAIN menjadi UIN. Beberapa kali saya menjadi saksi hidup seorang Azra yang tidak malu meminta dana buat pembangunan UIN atau mencarikan beasiswa bagi dosen-dosen muda kuliah lanjut di luar negeri.
Suatu ketika Azra pernah mengatakan bahwa ia tidak malu “meminta” bantuan kepada pihak lain karena toh penerima manfaat bukan dirinya, tapi kampus UIN atau dosen-dosen mudanya. Bahkan karena jerih payahnya Pemerintah Australia menjadikan UIN Jakarta sebagai salah satu targeted institution sehingga civitas akademika UIN akan diprioritaskan kuliah pascasarjana di kampus-kampus terkemuka di negeri Kangguru tersebut.
Keberhasilan saya mendapat beasiswa Australian Development Scholarship juga tidak lepas dari usaha Azra menjadikan UIN Jakarta sebagai targeted institution tadi.
Transformasi IAIN ke UIN membuat Azra tidak hanya dikenal sebagai intelektual yang produktif melahirkan karya-karya akademik, tapi ia juga memiliki jejak sukses dalam kepemimpinan dan manajemen lembaga. Ia ibarat Raja Midas, apapun yang disentuhnya menjadi emas. Sebelum menyulap IAIN menjadi UIN, Azra juga sukses membesarkan PPIM UIN Jakarta dengan Jurnal Studia Islamika-nya.
Amal jariyah Azra banyak. Entah berapa banyak dosen di Indonesia yang menikmati rekomendasi sakti seorang Azra sehingga sukses mendapat beasiswa kuliah atau training ke luar negeri. Setelah saya menunaikan tugas sebagai Presiden Mahasiswa, suatu ketika saya diundang ke ruang rektor.
Azra bertanya apakah saya berminat menjadi pemantau internasional dalam pemilu di Filipina tahun 2001. Tentu saja saya mengiyakan cepat. Tak lama kemudian saya mendapat undangan ke Filipina dengan biaya penuh dari Centre for Democratic Institutions (CDI), sebuah lembaga di bawah naungan Australian National University (ANU).
Satu rahasia kecil yang belum pernah saya sampaikan ke Azra adalah: uang saku dari CDI berhasil saya sisihkan untuk acara perkawinan saya. Bersama Prof Nurcholish Madjid, Prof Din Syamsuddin, dan Prof Nasaruddin Umar, Azra berkenan sebagai pengundang acara pernikahan saya di hari Sabtu 21 Juli 2001.
Ia datang ke resepsi pernikahan saya setelah acara Wisuda Mahasiswa IAIN/UIN. Azra bercanda, “Mahasiswa tingkat akhir datang wisuda hari ini, Burhan malah wisuda perkawinan.” Pada saat saya menikah, saya memang belum menyelesaikan kuliah saya di IAIN Jakarta.
Ia berpesan agar pernikahan saya tidak membuat saya lupa kuliah. Pesan Azra tersebut akhirnya saya tunaikan, bukan sekadar lulus S1, tapi juga gelar doktor saya raih dari kampus terbaik nomor satu di Australia.
Bagi saya, Azra adalah prototipe intelektual paripurna. Jejak kepemimpinannya di UIN Jakarta menorehkan prestasi yang melegenda. Di tengah kesibukannya yang berjubel, Azra juga tidak abai terhadap tugasnya sebagai intelektual publik dengan meladeni undangan-undangan seminar dan wawancara media massa.
Ia tak sungkan mengritik penguasa, termasuk rezim pemerintahan Jokowi yang dianggap berkontribusi atas menurunnya indeks demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia.
Sebagai intelektual par excellence, banyak karyanya yang berpengaruh besar. Di antaranya yang paling monumental adalah sumbangannya terhadap historigrafi Islam Indonesia yang menekankan pada pendekatan sejarah total (total history), yakni suatu metode totalitas dalam memahami suatu kejadian secara lintas-waktu, lintas-kawasan dan lintas-pendekatan.
Corak penulisan sejarah total ini Azra terapkan ketika meneliti ulama Nusantara yang tidak sekadar dibaca dalam konteks lokal, tapi juga dilihat dalam konteks jejaring global. Inilah sumbangsih besar Azra dalam studi sejarah Islam Indonesia pada khususnya, dan ilmu-ilmu sosial pada umumnya: sebuah kontribusi abadi yang akan terus mengalirkan pahala kepada dirinya