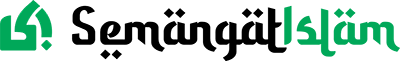Novi Budiman, S.IP, M.Si
Dosen Politik Islam UIN MY Batusangkar
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan bagian integral dari demokrasi di Indonesia, yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pemimpin lokalnya. Namun, di balik esensi demokrasi ini, terdapat fenomena yakni libido kekuasaan—sebuah istilah yang mencerminkan hasrat atau dorongan untuk berkuasa.
Secara teoritis, libido kekuasaan berakar pada konsep “will to power” yang dikemukakan oleh Friedrich Nietzsche, yang berpendapat bahwa hasrat untuk berkuasa adalah naluri mendasar dalam diri manusia. Dalam konteks politik, libido kekuasaan menjadi motor penggerak yang mendorong individu untuk mencapai posisi puncak kekuasaan.
Libido kekuasaan atau keinginan untuk berkuasa telah lama menjadi bagian tak terpisahkan dari politik. Max Weber, seorang sosiolog Jerman, dalam karyanya “Politics as a Vocation”, menjelaskan bahwa politik merupakan medan yang diisi oleh orang-orang dengan motivasi mendalam untuk menguasai alat-alat kekuasaan negara.
Dalam konteks Pilkada, libido kekuasaan ini semakin terlihat ketika para kandidat memperebutkan dukungan publik dengan segala cara, mulai dari kampanye yang memikat hingga strategi-strategi yang meragukan.
Hasrat untuk berkuasa ini bisa dikaitkan dengan teori “power dynamics” atau dinamika kekuasaan, yang dipopulerkan oleh Michel Foucault. Foucault berpendapat bahwa kekuasaan bukan sekadar alat represif, tetapi juga sebuah mekanisme yang membentuk relasi antarindividu.
Dalam Pilkada, dinamika kekuasaan tercermin dari cara kandidat mempengaruhi publik, membangun jaringan, dan menggunakan sumber daya politik dan ekonomi demi memastikan kemenangan mereka.
Namun, libido kekuasaan ini tidak selalu positif. Ketika dorongan untuk berkuasa mengalahkan komitmen moral dan etika, politik dapat berubah menjadi ajang pertarungan di mana segala cara menjadi sah untuk memenangkan kontestasi. Ambisi ini seringkali menyingkirkan nilai-nilai demokratis dan mereduksi proses Pilkada menjadi sekadar permainan kekuatan tanpa memperhatikan kepentingan rakyat.
Libido kekuasaan yang tak terkendali dapat membawa dampak buruk bagi demokrasi. Menurut teori Robert Michels dalam konsep “The Iron Law of Oligarchy”, semakin kuat hasrat seseorang atau kelompok untuk berkuasa, semakin besar kemungkinan terjadinya oligarki, di mana kekuasaan terkonsentrasi di tangan segelintir elit politik.
Dalam konteks Pilkada, seringkali kita melihat fenomena ini ketika kandidat-kandidat kuat dengan akses besar terhadap modal dan dukungan partai besar mendominasi kontestasi. Mereka menggunakan sumber daya politik, media, dan ekonomi untuk memanipulasi hasil Pilkada dan mempertahankan kekuasaan dalam kelompok yang sempit.
Selain itu, libido kekuasaan yang melampaui batas etika juga mengarah pada fenomena degradasi moral politik. Niccolò Machiavelli, dalam karyanya “The Prince”, menguraikan bahwa pemimpin yang kuat seringkali harus mengorbankan moralitas demi kekuasaan. Meskipun konteks ini digunakan dalam diskursus abad ke-16, relevansi Machiavellian dalam politik kontemporer tetap terasa, terutama ketika para politisi melakukan kompromi etis untuk menang.
Dalam Pilkada, kompromi ini bisa berupa politik uang, manipulasi opini publik, hingga pemanfaatan isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-Golongan) untuk memecah belah masyarakat demi kepentingan politik. Hasrat untuk berkuasa juga mempengaruhi cara para kandidat memobilisasi dukungan politik.
Teori Rasional Pilihan (Rational Choice Theory) yang dikemukakan oleh Anthony Downs dalam “An Economic Theory of Democracy”, menjelaskan bahwa aktor politik bertindak berdasarkan pertimbangan rasional untuk memaksimalkan kepentingan mereka.
Dalam Pilkada, para kandidat dan tim kampanye seringkali menggunakan pendekatan rasional ini untuk menyusun strategi elektoral yang dapat menjamin kemenangan. Misalnya, mereka mengidentifikasi kelompok pemilih potensial, merumuskan janji-janji politik yang sesuai dengan kebutuhan segmen-segmen tersebut, serta menggunakan media massa dan media sosial untuk memanipulasi persepsi publik.
Namun, pendekatan rasional ini seringkali mengabaikan aspek etis dan moral dari politik. Alih-alih fokus pada kebijakan yang berkelanjutan dan pro-rakyat, libido kekuasaan mendorong para kandidat untuk melakukan segala cara demi memenangkan Pilkada, termasuk strategi populisme, janji-janji semu, dan bahkan manipulasi politik uang yang membahayakan demokrasi.
Untuk menahan dampak negatif libido kekuasaan dalam Pilkada, perlu adanya penguatan sistem demokrasi yang menjamin transparansi dan akuntabilitas. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan memperkuat checks and balances, di mana lembaga-lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memegang peran penting dalam mengawasi jalannya Pilkada.
Teori Good Governance yang dipopulerkan oleh Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menekankan pentingnya keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam mengelola proses politik. Ketika institusi demokrasi kuat, libido kekuasaan para aktor politik dapat dikendalikan oleh sistem yang adil dan transparan.
Di sisi lain, pendidikan politik juga menjadi kunci penting dalam membatasi ruang gerak libido kekuasaan yang berlebihan. John Stuart Mill dalam bukunya “On Liberty” berargumen bahwa demokrasi yang sehat hanya dapat terwujud jika masyarakat terdidik secara politik. Masyarakat yang kritis akan lebih mampu menilai kualitas kandidat, memahami program-program politik, serta tidak mudah termanipulasi oleh hasrat kekuasaan para politisi.
Libido kekuasaan dalam Pilkada adalah fenomena yang tidak bisa dihindari, karena keinginan untuk berkuasa merupakan bagian dari dinamika politik. Namun, jika tidak dikendalikan, hasrat ini dapat merusak proses demokrasi, membawa degradasi moral politik, dan memunculkan oligarki baru di tingkat lokal.
Oleh karena itu, perlu adanya penguatan institusi demokrasi, pendidikan politik, serta penegakan hukum yang tegas untuk memastikan bahwa Pilkada tetap menjadi arena kompetisi yang sehat dan bermartabat. Hanya dengan demikian, kekuasaan tidak lagi menjadi tujuan akhir, melainkan sarana untuk melayani rakyat dan memajukan daerah.
Daftar Pustaka
Weber, M. (2015). Politics as Vocation. In T. Waters, & D. Waters, Weber’s Rationalism and Modern Society (pp. 129-198). New York: Palgrave Macmillan.
Nietzsche, F. (1968) The Will to Power. Terjemahan Walter Kaufmann dan R.J. Hollingdale. New York: Vintage Books.
Downs, A. (1957). An Economic Theory of Political Action in a Democracy Author (s): Anthony Downs Published by : University of Chicago Press Stable URL :http://www.jstor.org/stable/1827369 Accessed : 29-02-2016 20 : 13 UTC Your use of the JSTOR archive indicates your ac. 65(2), 135–150.
Machiavelli, N. 2008. The Prince. Surabaya: Selasar
Mill, John Stuart. 2001. On Liberty atau Perihal Kebebasan, terj. Alex Lanur. Canada: Batoche Book Limited.