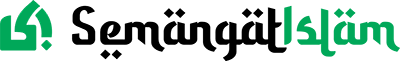Oleh: Dr. Jasra Putra
(Kadivwasmone KPAI)
Tampilnya SJ di publik, membawa penolakan sejumlah masyarakat, terutama masyarakat mengingatkan update kondisi penanganan para korban pedofilia yang tidak terdengar.
Terutama penolakan masyarakat, tentang eksisnya sejumlah lembaga penyiaran menampilkan SJ di publik. Ada kekhawatiran dengan tampilnya SJ akan membawa trauma korban bangkit kembali dan berkepanjangan.
Sehingga situasi situasi seperti ini, ketika pelaku pedofilia dipertontotonkan, tetapi disisi lain ketika di pertontonkan Negara tidak beranjak serius menangani dan menjamin para korban.
Karena dalam survey KPAI di beberapa lembaga rehab Negara, tidak ada yang tuntas penanganannya. Artinya harus ada upaya lebih dari Negara, dibanding UU Penyiaran membiarkannya.
Setidaknya KPAI memotret 3 kasus pedofilia pada proses hukum dan penanganannya.
Pertama anak anak NTT yang diperjualbelikan bisnis pedofilia di puncak Cianjur, yang akhirnya di reunifikasi ke keluarganya oleh Kementerian Sosial. Kedua, kasus Brother Angelo yang melakukan pedofilia pada anak anak asuhnya, namun di lepaskan Kepolisian.
Ketiga, kasus SJ yang bisa menyuap aparat hukum dan di pertontonkan kepada publik, tanpa kita tahu bagaimana situasi para korban sekarang.
Mari kita membahasnya satu persatu.
Pertama, anak anak NTT yang awalnya di ajak merubah nasib dan dorongan orang tuanya juga untuk mendapatkan masa dpean yang lebih baik. Kemudian ada orang yang mengajaknya untuk merantau, karena alasan anak tidak ada masa depan di Kampung.
Kemudian mereka terlepas dari orang tua dengan alasan akan dipekerjakan, dan kemudian sempat tinggal shelter, namun shelter tersebut tidak terurus dan bubar. Akhirnya anak anak ditangkap pasar kejahatan anak, dengan memperkerjakan mereka dalam bisnis pedofilia.
Dengan tidak ada pilihan keluar, karena bisa tidak selamat. Namun karena satu anak bisa melarikan diri dari jaringan kejahatan anak tersebut, kita bisa mengungkapnya.
Kedua, seorang ruhaniawan Brother Angelo yang bergerak sosial, mendirikan panti di Depok, kemudian melakukan pedofilia kepada anak anak yang di asuhnya selama 5 tahun. Namun seusai anak anak bersaksi dan pelakunya dipenjara, hanya dalam hitungan tempo 2 bulan pelakunya dilepaskan. Dengan berbagai alasan Polres Depok mengeluarkan dari penjara pada waktu itu.
Di tengah perjalanan proses hukumnya, kepolisian juga menggangap sulit ditangani, karena yang mengalami anak anak panti, karena tidak ada wali yang bisa bertanggung jawab, apalagi pengasuhnya berhadapan masalah hukum. Di tambah selepas tidak di panti, mereka tidak mengetahui anak anak tinggal dimana.
Sehingga dukungan untuk anak anak terus mempertahankan kesaksiannya sangat sulit dikawal, justru anak terlunta lunta, berpindah pindah, terbengkalai. Sehingga karena alasan tersebut, proses hukum tidak bisa dilanjutkan. Dengan alasan anak anak tidak ada, tidak bisa dilanjutkan kasusnya.
Lebih parahnya lagi para korban melaporkan kepada Kementerian Sosial, mereka ditakuti oleh pelaku dan kroninya. Tentu ini menjadi kekecewaan bersama dalam penanganan pedofilia. Di dalam penjara pun masih bisa menakuti anak, dan keluarga pelaku sempat datang ke KPAI, untuk meminta pelakunya dibebaskan dan anak anak mencabut kesaksiannya. Namun sekarang pelaku sudah dalam penjara kembali.
Ketiga, penolakan masyarakat atas masifnya pemberitaan pelepasan SJ dari penjara, yang cenderung seperti heroik, sehingga lebih nampak kasusnya mengada ngada. Ditambah kondisi para korban yang mungkin masyarakat belum update penanganannya. Sehingga pelepasan SJ diiringi kasus suap kepada aparat hukum, menjadi penolakan masyarakat.
Dari kondisi tersebut, ada beberapa hal yang harus kita lihat lebih jeli dan dalam.
Pertama sikap permissif, ketiga penanganan kasus tersebut menandakan secara gamblang, bahwa keberpihakan kepada para korban menjadi pekerjaan berat.
Kedua, stigma pedofilia adalah juga terkait anggapan isu LGBT. Yang ternyata lebih berat memberi dampak stigma ke para korban. Yang tentu menyebabkan pembahasannya cenderung dijauhkan, penolakan yang tidak pada tempatnya, menyebabkan masyarakat berperilaku salah kepada isu ini. Sehingga kasus kasus seperti ini, mudah masuk angin, karena minimnya dukungan pilar demokrasi.
Alih alih menyelamatkan, tapi menghancurkan sisi kemanusiaan itu sendiri dengan stigma korban pedofilia. Seperti di masa pandemic terungkap, mereka yang paling teringgal soal penanganan pandemic, terutama akses vaksin, karena rata rata tidak memiliki NIK.
Belum lagi kalau menarik jauh ke belakang, tentang situasi anak anak yang pada tumbuh kembangnya memiliki fisik yang berbeda. Sedangkan jaminan untuk merubah fisik dan menentukan gender, masing sangat mahal dan tidak terjangkau. Sehingga lebih memperlihatkan mereka menjadi pesakitan dalam tumbuh kembangnya. Bahkan tidak aman tampil di depan umum.
Ketiga, Rehabilitasi masih belum tuntas. Hasil survey KPAI atas pelaksanaan rehab di lembaga rehabilitasi pemerintah yang masih belum tuntas. Dan membutuhkan anggaran yang besar. Apalagi kalau melihat kasus brother Angelo, dengan anak anak tidak terurus dalam kasusnya.
Karena dari kasus ini, lebih memperlihatkan, kita belum punya shelter yang representatif dan para petugas yang capable, apalagi ada ketakutan atau stigma menangani anak seperti ini (menular). Sehingga seringkali rehab dan penanganannya salah kaprah.
Keempat, dengan kondisi seperti ini, pertanyaannya, dimana para korban. Yang parallel dengan itu, tentu membawa trauma berkepanjangan, dalam potret kita mengani korban pedofilia di Indonesia yang masih seperti ini.
Keempat, artinya secara jaringan dan sistem kerja pelaku kejahatan pedofilia sangat jeli melihat situasi anak anak seperti ini. Sehingga dengan segala skenario yang mereka buat, bisa menempatkan anak anak dalam perlakukan salah dan eksploitasi ekonomi. Bahkan menjadi ancaraman generasi.
Tentunya dengan kondisi ini, apa yang harus kita revatilisasi bersama sama dalam membantu anak anak korban pedofilia. Tentunya dengan beberapa kasus ini, semakin memperlihatkan bagaimana penanganan kasus pedofilia di Indonesia, mulai aparat hukumnya disuap, melepaskan pelaku, dan keberpihakan yang tidak tepat.
Sehingga memang perlu ekstra luar biasa Negara untuk benar benar tegak berdiri dan tegas dalam penanganan pelaku dan kondisi para korban yang masih sangat jauh dari sistem perlindungan.
Setelah melihat kondisi ini, sudah seharusnya kita sadar dan komit mendorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang pernah disampaikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada para legislator.
Agar ada penanganan yang lebih obligation dari Negara untuk mengawal dan solusi permanen berkepanjangan.
Artinya kalau boleh tidak dikatakan kalah, KPPPA harus lebih maju dan progressif mendorong RUU ini bersama masyarakat pemerhati yang prihatin pada kejahatan seksual di Indonesia. Tentu dengan dukungan semua pihak. Sehingga keinginan menyelamatkan korban hingga tuntas dapat terwujud.
Saya kira dengan SJ melihat situasi ini, harusnya SJ lebih arif dan peduli kepada situasi penanganan fedofilia di Indonesia.Terutama dengan berpihak kepada para korban, mengurangi trauma. Tidak mengulangi menyuap aparat.
Kita masih berharap pemerintah dan legislator mau menganggarkan dan memajukan proses pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan tidak masuk angin lagi. KPAI menganggap penting penanganan lebih komperhensif kepada para korban, keperpihakan dari pelaku kejahatan seksual.
Sudah seharusnya ketiga kasus pedofilia ini mengasah sisi kemanusiaan, jadi potret penanganan pedofilia yang masih permissif dan jauh dari keadilan di Indonesia.
Harus segera berevolusi untuk memihak para korban dan penanganan pelaku yang terawasi berkelanjutan, agar anak anak tidak terjebak lebih jauh lagi dari perlakuan salah kita semua selama ini, dalam melihat kasus kejahatan fedofilia anak.