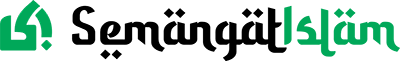Novi Budiman, S.IP., M.Si
Dosen Prodi Politik Islam UIN MY Batusangkar
Dalam kontestasi politik di era digital ini, panggung Pilkada bukan lagi sekadar arena bagi para calon kepala daerah untuk adu visi dan misi. Fenomena baru yang kini turut mewarnai adalah kehadiran para buzzer—sekumpulan individu yang berperan sebagai “pendukung bayangan” di media sosial. Para buzzer ini memanfaatkan platform digital untuk menciptakan narasi yang mendukung calon tertentu atau menghancurkan reputasi lawan politiknya.
Keberadaan buzzer di panggung Pilkada seolah-olah menjadi “senjata rahasia” bagi para calon. Dengan kecanggihan teknologi dan kemudahan akses internet, mereka dapat dengan cepat menyebarkan informasi, baik yang valid maupun hoaks, kepada khalayak luas. Kecepatan dan volume informasi ini sering kali menjadi senjata utama para buzzer untuk membentuk opini publik, bahkan sebelum masyarakat sempat mencerna kebenaran dari informasi yang diterima.
Fenomena ini tidak hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga tentang menciptakan ilusi. Buzzer sering kali memanipulasi fakta atau bahkan menyebarkan hoaks untuk mengarahkan persepsi publik. Dengan teknik ini, mereka menciptakan realitas alternatif yang bisa memengaruhi pilihan pemilih. Alih-alih berfokus pada program kerja dan visi yang ditawarkan, pemilih justru terjebak dalam perang informasi yang tidak sehat.
Namun, politik para buzzer bukan tanpa dampak negatif. Pertama, politik semacam ini cenderung mengedepankan isu-isu yang bersifat sensasional ketimbang substansial. Diskursus publik sering kali didorong untuk lebih fokus pada isu-isu permukaan, seperti skandal pribadi atau serangan karakter, daripada membahas program nyata yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Akibatnya, kualitas demokrasi di tingkat lokal bisa tergerus oleh permainan opini yang dangkal.
Kedua, bazerian yang tidak bertanggung jawab sering kali memanfaatkan kekuatan anonim mereka untuk menyebarkan hoaks atau fitnah. Hal ini tidak hanya merusak reputasi individu atau kelompok tertentu, tetapi juga berpotensi memecah belah masyarakat. Dalam konteks Pilkada, ini bisa berarti terciptanya polarisasi yang semakin tajam di antara pendukung calon-calon yang berbeda.
Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa peran buzzer dalam politik modern cukup signifikan. Mereka mampu menggerakkan massa, membentuk persepsi publik, dan, dalam beberapa kasus, menentukan arah kampanye. Namun, pertanyaan mendasar yang perlu kita renungkan adalah: Apakah kehadiran para buzzer ini memperkuat atau justru melemahkan demokrasi?
Untuk mencegah dampak negatif dari politik para buzzer, diperlukan literasi digital yang kuat di kalangan masyarakat. Pemilih harus dibekali dengan kemampuan untuk menyaring informasi, memahami konteks, dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang belum tentu benar. Selain itu, regulasi yang lebih ketat terhadap praktik-praktik penyebaran hoaks di media sosial juga sangat diperlukan.
Di akhir, kita perlu ingat bahwa demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang didasarkan pada diskusi yang konstruktif, bukan pada narasi yang dibentuk oleh para buzzer demi kepentingan sesaat. Dalam panggung Pilkada, kita seharusnya fokus pada kualitas calon dan program yang mereka tawarkan, bukan pada permainan bayangan yang dimainkan oleh para bazerian di belakang layar.