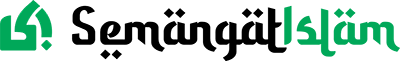Oleh: Dr. Syahrir Karim*
Ketua Prodi Ilmu Politik UIN Alauddin Makasar
Semangat Islam – Konsep multicultural sendiri bermakna keberagaman. Jika pluralisme hanya menggambarkan suatu masyarakat yang beragam, baik etnis, agama, bahasa, ras dan budaya yang berbeda. Maka konsep multikultaralisme lebih jauh lagi menjelaskan bahwa dalam perbedaan itu terdapat persamaan di ruang public.
Multikulturalisme merupakan sebuah gagasan bukan hanya mengakui keberagaman, akan tetapi juga berusaha mencoba mengelola perbedaan dan keberagaman tersebut agar lebih terarah. Terlepas dari perbedaan tersebut, bahwa pluralisme dan multikultaralisme tetap menjunjung semangat untuk menerima kelompok lain yang berbeda dalam system sosial tanpa melihat perbedaan dalamnya.
Perbedaan dan keberagaman dalam suatu sistem sosial terdapat potensi konflik yang sewaktu-waktu bisa muncul. Gagasan tentang multikultaralisme sendiri terkait erat dengan pengaturan relasi antara kelompok mayoritas dan minoritas, masyarakat adat, dan lainnya. Apabila suatu masyarakat yang secara sosiologis dihuni oleh penduduk yang berbeda agama dan suku atau etnik, maka perbedaan itu potensial memicu munculnya konflik dan kekerasan.
Oleh karena itu, mengelola potensi konflik yang ada adalah hal yang mesti diantisipasi sejak dini termasuk dengan cara memahamkan pentingnya multikultaralisme di tengah masyarakat. Dalam konteks sejarah, sebenarnya multikulturalisme berawal dari perjuangan politik yang menuntut persamaan hak yang dilakukan oleh migran kulit hitam dari Afrika di Amerika. Mereka menuntut untuk dihargai kebudayaannya, tidak harus sama dengan kebudayaan orang kulit putih.
Secara historis sebenarnya bangsa Indonesia tradisi silang budaya yang cukup meneguhkan bagaimana Indonesia (nusantara) di masa lalu begitu mapan dengan keberagaman. Denis Lombard (2000) dalam Nusa Jawa Silang Budaya begitu apik menjelaskan bagaimana Indonesia di masa lalu diwarnai dengan hubungan antar etnis dan ras dengan perbedaan budaya masing-masing.
Diceritakan bagaimana bangsa Arab, Cina, India, dan bangsa-bangsa lain datang ke Nusantara berdagang lalu kemudian menetap.Nusantara di masa-masa awal terbangun sebuah system social yang begitu ramah di tengah silang budaya seperti bahasa Lombard. Barulah kemudian system social yang multicultural ini terganggu ketika kedatangan para panjajah yakni kolonialisme Belanda. Keberadaan bangsa colonial ini seakan membawa arogansi budaya yang menenmpatkan budaya nusantara yang multicultural itu sangat tradisonal atau tertinggal.
Bagi mereka, kebudayaan barat jauh lebih maju dibandingkan budaya dari belahan dunia dari Timur khususnya warga tempatan atau bumiputra. Padahal jauh sebelum bangsa penjajah datang nusantara sudah terbangun system social yang rapi dimana para pendatang mampu berasimilisi dengan budaya lokal dan hidup rukun.
Dalam sejarah peradaban Islam pun demikian ketika Islam datang di tanah Arab yang mampun berasimilasi dengan budaya lokal yang ada. Islam datang tidak begitu saja mengharamkan dan melarang tradisi-tradisi lokal bahkan yang berlawanan dengan agama Islam sekalipun walaupun pada akhirnya berangsur-angsur diatur secara khusus.
Islam datang dan melakukan ekspansi “kekuasaan” tidak untuk menaklukkan dan memaksa bangsa-bangsa yang kalah tersebut untuk masuk Islam dan menjajah. Akan tetapi jusru sebaliknya, Islam datang “memerdekakan” mereka dari cengkraman “bangsa-bangsa colonial” yang menjajah mereka selama ini termasuk menjajah secara budaya.
Islam datang sebagai pemersatu dan perekat masyarakat hetergogen yang sebelumnya tidak pernah bersatu. Para penakluk Arab yang selama ini didominasi oleh Barat runtuh dan penaklukan Islam bisa dipandang sebagai penyatuan kembali wilayah-wilayah mereka yang selama ini retak. Pada akhirnya, bangsa-bangsa Timur di bawah pengaruh Islam telah bangkit dan kemudian menegaskan dirinya sebagai bangsa merdeka yang selama berabad-abad dibawah dominasi Barat (Hitti, 2002).
Ulasan di atas menjadi argument singkat bagaimana Islam secara khusus merespon gagasan multikultaralisme ini. Multikulturalisme sendiri berangkat dari sebuah wacana yang secara serius merespon keberagaman kelompok etnik, agama maupun kelompok-kelompok lainnya. Rasa ke’aku’an terkadang menggeser hak-hak minoritas. Bahwa rasa ‘kami’ lebih banyak dibandingkan ‘anda’ yang lebih sedikit masih nampak jelas di era demokrasi ini.
Multikulturalisme sendiri berusaha mewujudkan sebuah praktik kewarganegaraan (citizenship) yang lebih demokratis, yakni pentingnya ruang public yang mengakui hak-hak individu serta rasa kesederajatan yang sama sebagai identitas kolektif. Jadi, kalau hari ini masih ada yang mempersoalkan isu-isu etnisitas, ras, dan agama untuk kepentingan politik tertentu berarti dalam diri mereka sebenarnya bersemayam darah kolonialisme.
Yakni kelompok penjajah yang selalu mau mendominasi, memaksakan kehendaknya dan yang lainnya dianggap salah. Tau sendiri kan, penjajah ini tempatnya di mana? Selain Islam tidak membenarkan, UUD 45 pun jelas menegaskan …” penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan..”