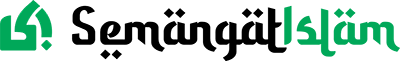Oleh : Asratillah
(Direktur Profetik Institute)
Dua malam lalu, saya bersua secara virtual dengan adik-adik dari DPD IMM Kaltara. Selain membincang tentang peluang dan tantangan yang dilahirkan oleh Era Disrupsi, momen tersebut adalah kesempatan tuk bertemu lagi dengan beberapa kawan yang sudah lama tidak saling jumpa.
Salah satu kawan yang saya maksud adalah Bung Herman bin Mirwan, kami aktif bersama di Ikatan Remaja Muhammadiyah Kota Parepare di tahun 90-an hingga awal millenium ke dua, tapi akhirnya dia memilih tuk merantau ke Nunukan.
Istilah disrupsi bukanlah barang baru, cuman baru diperbincangkan banyak orang dan menjadi bagian dari trend intelektual di sekitaran tahun 2018 an hingga saat ini (karena Pandemi Covid-19 oleh sebagian pihak dianggap sebagai salah satu bentuk disrupsi).
Disrupsi seringkali diasosiasikan dengan kejutan-kejutan, ke tak-terduga-an, ke tiba-tiba an, dimana semua hal tersebut membuat kita menjadi kelabakan.
Bahkan konon tidak sedikit di antara kita, yang mengalami “kejang-kejang” alias “epilepsi” kebudayaan (kalau kita meminjam istilah Yasraf Amir Pilliang dalam “Dunia Yang dilipat”), dikarenakan kapasitas dan respon kebudayaan yang kita punya, tak mampu mengantisipasi kecepatan perubahan yang terjadi.
Di tahun 70-an, terbit buku yang dijuduli “The Innovator Dillema”, ditulis oleh seorang guru besar dari Harvard Bussines School, yang bernama Clayton M. Christensen. Buku tersebut bercerita mengenai tragedi dan ironi dalam dunia bisnis,
Christensen melihat adanya gejala kekalahan para petahana bisnis (incumbent) saat bersaing dengan para pendatang baru. Padahal dilihat dari segi kepemilikan modal dan sumber daya manusia, para petahana lebih punya segala-galanya dibanding pendatang.
Tapi bak memenuhi ramalan Darwin si empu teori evolusi, yang memenangkan permainan bukanlah mereka yang paling punya segala-galanya, tetapi yang paling bisa beradaptasi dengan lingkungan.
Begitu pula dalam bisnis, yang bisa bertahan hidup bahkan menjadi pemenang, adalah yang paling bisa beradaptasi dengan situsai lingkungan bisnis teranyar. Para petahana bisnis juga terus melakukan inovasi kata Christensen,
tetapi inovasi yang mereka lakukan hanya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan omset dan perluasan ekspansi pasar yang sudah disegmentasi sebelumnya. Namun para pendatang mereka melakukan inovasi pada hal yang lebih mendasar yakni model bisnis.
Inovasi pada model bisnis ini bisa kita lihat dengan jelas pada bisnis perhotelan dan jasa transportasi, di mana terhadi pergeseran dari model bisnis “owner economy” ke “sharing economy”.
Para pemain lama dalam dunia perhotelan, akan memulai bisnisnya dengan jumlah capital yang sangat besar, karena mesti membangun bangunan yang representatif dengan jumlah kamar banyak tentunya, hingga mempekerjakan karyawan yang tidak sedikit.
Tetapi pemain baru jasa penginapan semisal OYO, RedDorz dan semacamnya hanya menggunakan modalnya untuk membuat wadah aplikasi dimana bisa mempertemukan antara orang yang membutuhkan kamar dan orang-orang yang memiliki sisa kamar di rumah dan tidak digunakan, tetapi bisa disulap senyaman kamar hotel.
Pemain baru jasa penginapan tak mesti membuat satu gedung dan memiliki banyak kamar, tetapi mengkolaborasikan banyak pemilik kamar.
Inovasi model bisnis ini oleh Crhistensen disebut sebagai karakteristik pertama dari disrupsi. Karakteristik kedua adalah , disrupsi dalam dunia bisnis bermula dari pasar level bawah (low end).
Artinya kejuatan-kejuatan bisnis menyasar segmen masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah, berbeda dengan para pelaku bisnis lama yang pasarnya adalah kelas ekonomi menengah ke atas.
Di jasa transportasi misalnya, perusahaan-perusahaan seperti Gojek, Grab, Maxim awalnya menyasar kalangan pendepatan menengah ke bawah, menyasar para ibu-ibu yang ingin ke pasar tradisional, menyasar anak-anak kuliahan yang ingin ke kampus.
Berbeda dengan perusahaan taksi konvensional, yang memang menyasar para manajer, kaum eksekutif, orang gedongan dan sebagainya. Penyedia jasa transportasi online dalam iklan-iklannya mengasosiasikan diri dengan “orang-orang biasa”, sedangkan perusahaan-persuahaan taksi memang mencitrakan diri melayani kelas ekonomi menengah ke atas.
Tapi kajian tentang disrupsi tidak hanya sekaitan bisnis saja, tapi juga merembes ke bidang-bidang lain semisal komunikasi. Bahkan Christensen seringkali mengasosiasikan antara disrupsi dengan perkembangan komunikasi digital.
Tapi Paul Paetz berpendapat, perkembangan komunikasi digital justru menjadi faktor pendorong bagi lahirnya disrupsi. Banyak kajian tentang disrupsi sekaitan dengan ini, semisal yang berkaitan dengan e-commerce,
lalu kehadiran media online yang awalnya berupaya menyuguhkan informasi ke khalayak dengan cara murah dan mudah, belum lagi disrupsi dalam hal komunikasi marketing yang juga banyak digunakan dalam bidang politik.
Tapi kita juga perlu mempertimbangkan gagasan dari Francis Fukuyama yang dia tuangkan dalam buku “The Great Disruption ; Human Nature and the Reconstitution of Social Order”.
Francis Fukuyama seakan-akan ingin mengatakan bahwa disrupsi (terutama dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan), merupakan sesuatu yang ambivalen.
Disatu sisi, disrupsi mengintrupsi beberapa bentuk kemapanan lama, membuka keran kebebasan, memungkinkan kesetaraan dalam kehidupan bernegara, mendorong terjadinya demokratisasi, mendorong perkembangan sains dan teknologi serta meningkatkan sensitifitas warga dunia akan isu-isu HAM dan ekologi.
Tapi disi lain disrupsi juga mengakibatkan kekacauan (disorder). Kriminalitas bukannya berkurang tetapi semakin bertambah baik dalam jumlah maupun bentuk terutama di daerah perkotaan, bahkan lahir bentuk tindak kriminal yang hanya dimungkinkan oleh adanya perkembangan komunikasi digital yang biasa disebut dengan istilah “cybercrime”
(termasuk juga sebenarnya di sini beberapa gejala Post-Truth yang biasa kita kenal dengan hoax, fakenews, hatespeech dan sebagainya). Beberapa institusi sosial yang menjadi penyedia jejaring pengaman nilai runtuh satu per satu, keluarga tidak lagi menjadi oase, konsep keluarga tradisional seakan-akan ditantang,
orang tua tidak lagi menjadi satu-satunya otoritas simbolik awal pada anak-anak, kini ada berbagai rupa media sosial yang juga menjadi semacam patron nilai dan gaya hidup anak-anak. Kualitas pendidikan tak kunjung membaik,
bahkan tak jarang pendidikan hanya menjadi semacam lembaga yang mengkonpensasi ketidakefektifan keluarga dalam mendidik anak-anak, perceraian semakin tinggi, dan sebagainya.
Lalu bagaimana dengan Pandemi Covid ? menurut saya dan menurut sebagian adik-adik yang menjadi peserta diskusi malam itu, menganggap pandemi juga adalah sebuah disrupsi. Mungkin saja disrupsi menunjukkan bahwa sejarah tidak berjalan secara linear tetapi dialektis,
maksudnya jalannya sejarah tak selalu mudah untuk ditebak. Saat modernitas mulai menyingsing, manusia begitu optimis dengan nasibnya, dan ini bisa kita lihat dari gagasan-gagasan seperti Turgot, Condorcet, Comte dan lain-lain di awal abad 18 dan 19.
Perang dunia I dan II, sempat menyadarkan kita bahwa optimisme akan kemajuan nasib manusia, tak bisa lepas sepenunhnya dari ke-serigala-an manusia yang siap “mengigit” sesamanya. Awalnya kita mengigit dengan tangan, batu, panah, pedang dan tombak.
Tapi lama kelamaan kita mengigit dengan senapan mesin, hulu ledak nuklir, pesawat jet, senjata biologis hingga jeratan utang.
Kalau dalam buku Christensen yang terkejut adalah para petahana bisnis, dalam situasi pandemi yang menjadi petahana bisa jadi kita sebagai spesies, sebagai satu kesatuan umat manusia. Selama ini kita berinovasi yah hanya untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi kita, mempertahankan pendapatan domestic bruto kita dan semacamnya.
Kita tidak berinovasi dalam rangka mengubah “model relasi” kita dengan alam, habitat spesies lain kita habisi digantikan dengan bangunan beton, hutan dibabat, laut dan sungai dicemari.
Dengan sedikit memilintir gagasan Christensen, pandemi tidak hanya disrupsi yang menuntut merubah “model bisnis” tetapi juga menuntut perubahan “model relasi”.
Relasi antar ras yang berbeda, relasi antar pemeluk yang berbeda, relasi antar negara maju dan berkembang, relasi antara negara dengan warga negara, relasi antara si kaya dan si miskin, dan relasi antara manusia dengan entitas ekologis lainnya (biotik maupun a-biotik). Soal bagaimana “model relasi” yang tepat ? itu butuh diskusi panjang tentunya.