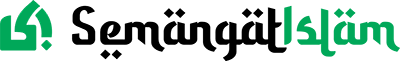Oleh: Zulfan Tadjoeddin
Setelah membalik-balik buku “Dark Academia: How Universities Die” karya Peter Fleming yang terbit belum lama ini, dan memantik diskusi hangat di kalangan akademis dalam beberapa pekan terakhir, ingatan saya melayang ke masa silam.
Ke satu pagi yang cerah di awal September 2014.
Saat itu saya tengah menikmati rehat kopi yang sedap di Scandic Marina Congress Centre di Helsinki, Finlandia. Saya melepaskan pandangan ke arah kapal dan ferry yang berlalu-lalang di pelabuhan.
Di awal musim gugur itu, saya sedang menghadiri sebuah konferensi di WIDER (World Institute of Development Economic Research). Saya membatin, bagus juga nih untuk difoto. Lalu saya minta tolong seseorang. Saat itu, saya belum bisa selfi. Orang tersebut juga minta difoto. Lalu dia nanya, “kamu dari mana”. Saya jawab, “Indonesia”. Saya balik nanya, “kalau kamu?” Dia jawab, “Canada”.
Lalu saya lihat name-tag yang tergantung di leher-nya, “you are Jacques Bertrand, I know you”. Dia pun memelototi name-tag saya, “you are Zulfan Tadjoeddin, I know you too”.
Lalu kita sama-sama tertawa dan obrolan berlanjut dengan enak.
Ternyata kita sudah saling mengenal dari tulisan masing-masing. Bertrand menulis buku “Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia” (CUP, 2004). Buku itu sering saya kutip.
Dia adalah professor ilmu politik di University of Toronto. Dia mungkin membaca tulisan saya tentang konflik. Beberapa hari di Helsinki, saya sempat pelesir seharian ke Tallinn, ibu kota Estonia, negara kecil pecahan Uni Soviet. Helsinki – Tallinn dipisahkan oleh Gulf of Finland dan hanya berjarak dua jam perjalanan dengan ferry.
Sempat pula ikut makan malam di Wisma Indonesia di Helsinki. Kedutaan RI di luar negeri biasa mengundang makan peserta konferensi dari Indonesia, sesuatu yang juga saya alami di Lisbon (Portugal) setahun sebelumnya.
Dari Helsinki, saya sempatkan pula terbang Belanda. Di Schiphol, saya dijemput Iman K. Nawireja yang sedang PhD di Wageningen. Kami naik kereta ke Den Haag, lanjut dengan taxi ke hotel yang sudah disiapkan oleh kolega di ISS (Institute of Social Studies).
Kolega ini juga sudah menyiapkan sebuah seminar untuk saya esoknya di kampus ISS. Aloysius Gunadi Brata yang sedang study PhD di Amsterdam hadir di seminar itu.
Taxi di Den Haag menggunakan sedan jenis Mercedes. Saya bayar 20 Euro untuk jarak sekitar 5km. Mihil memang, tapi tak apa, tinggal di-reimburse, kan perjalanan dinas.
Saya terbang dari Sydney ke Helsinki dengan dua jam transit di Singapore. Perjalanan panjang yang melelahkan, separo lingkar bumi. Penerbangan pulang dari Helsinki ke Sydney melalui transit di Hong Kong.
Trip saya ke Eropa saat itu menggunakan berbagai macam maskapai: Qantas, Finnair dan Cathay Pacific. Tiket saya dibayarin kampus (WSU), hotel di Helsinki ditanggung WIDER, akomodasi di Den Haag di traktir oleh ISS.
Kehidupan akademis telah membawa saya ke puluhan negara di lima benua dan menginjakkan kaki di hampir semua propinsi di tanah air. Dunia akademis yang saya lakoni sejak 14 tahun terakhir di Australia telah memberikan kehidupan yang cerah, cukup menyenangkan.
Saya kira, jika dibandingkan dengan kehidupan akademis di tanah air, maka kehidupan akademis di Australia akan terlihat begitu benderang. Saya –dan sepertinya banyak kolega yang setuju– akan mudah melihat sisi terang kehidupan akademis di Australia.
Masalahnya, ya itu tadi, Peter Fleming menulis buku “Dark Academia”.
Dia bilang sesuatu yang kelam. Dia menggugat kehidupan dunia akademis yang tampaknya sudah ajeg.
Saya sebenarnya paham maksud Fleming. Tapi kok bisa-bisanya yang saya ingat malah trip yang asyik ke Eropa itu? Ingatan ini seolah mendurhakai pemahaman saya sendiri.
Padahal Fleming sudah meneguhkan hatinya untuk menjelaskan dampak arus besar neoliberalisme terhadap dunia perguruan tinggi di Barat, terutama di Inggris, AS dan Australia.
Fleming menuliskan pengamatan dan analisisnya terhadap dunia akademis yang dia geluti hingga mencapai jenjang tertinggi, professor. Dia menilai, universitas telah menjadi sangat korporatis dan komersil. Kadar “public-goods” dari universitas terus tergerus. Mahasiswa dilihat sebagai konsumen yang harus dilayani dan dipuaskan, sementara dosen adalah faktor produksi yang makin teralienasi dari dunianya yang ideal.
Sekali lagi, saya paham maksud Fleming. Saya melihat dari dekat dan bahkan mengalami langsung apa yang dijelaskan Fleming. Mungkin kenangan tentang Helsinki dan dan kota-kota Eropa itu adalah respon seketika yang hendak menguji kadar kegelapan “Dark Akademia”nya Fleming. Lantas seperti apa sebenarnya “Dark Academia” Fleming itu?
Sila bergabung di sebuah diskusi yang akan digelar oleh Dewan Guru Besar (DGB) IPB, Jumat 10 September 2021, pukul 14.00 WIB. Di acara itu, saya akan mendampingi guru saya KangMasProf Arya Hadi Dharmawan. Ini merupakan perintah dari guru saya Prof Sonny Priyarsono.
Ngomong-ngomong, soal “gelap” dan “terang” sebenarnya sangat relatif. Tergantung dari sisi mana kita melihat. Sinar pelita akan terlihat terang ketika dilihat dari kegelapan. Sebaliknya, pelita itu akan terlihat gelap saat dilihat dari ruangan yang bertabur sinar petromak. Ide tulisan singkat ini muncul saat saya sedang menggosok dua toilet di lantai atas rumah saya tadi pagi.
Dilihat dari perspektif seorang dosen atau professor NKRI, mungkin dia akan melihat betapa “gelap”nya kehidupan seorang dosen di Sydney: masih harus membersihkan toilet di Minggu pagi, di awal musim semi ceria.
Atau, bisa jadi “gelap” atau “terang” itu sebenarnya tidak terlalu penting.