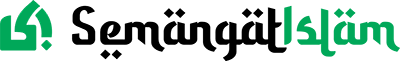Oleh: Amin Mudzakkir
(Peneliti BRIN LIPI & Dosen Unusia Jakarta)
Mungkin tidak ada kata-kata yang lebih kuat pengaruhnya dalam wacana intelektual dan politik kontemporer daripada keberagaman kultural. Setidaknya ini terjadi sejak 1980-an dan terus berlangsung hingga sekarang. Saking kuatnya, orang-orang terlihat sudah tidak mampu lagi melihatnya secara kritis, sehingga seolah-olah keberagaman kultural adalah satu-satunya tujuan yang harus diperjuangkan.
Di Indonesia, kata-kata keberagaman kultural yang sering dipertukarkan dengan istilah kebhinekaan itu membetot perhatian tidak hanya para aktivis sosial, tetapi juga pemangku kebijakan. Rasanya kurang afdol jika mereka tidak berpidato atau menulis karya ilmiah tanpa menyebut arahan tentang pengtingnya kita semua menerima keberagaman kultural.
Para agamawan ikut serta di dalamnya dengan mengatakan bahwa keberagaman kultural adalah sunnatullah yang tidak bisa dan tidak boleh disangkal. Tetapi apa sesungguhnya keberagaman kultural itu? Apa yang mesti kita perbuat dengan kata-kata itu? Mengapa ia begitu penting dan bahkan dianggap menjadi satu-satunya masalah yang harus diperjuangkan?
Jarang disadari bahwa kata-kata keberagaman kultural lahir dari suatu pergeseran paradigma keadilan. Sebelum 1980-an, keadilan lebih banyak dipahami dengan pertanyaan tentang bagaimana sumber daya sosial-ekonomi dibagi (redistribusi, tetapi sejak 1980-an pertanyaannya berubah menjadi bagaimana keberagaman kultural diakui (rekognisi). Lalu apa masalahnya dengan pergeseran ini?
|
Pertanyaan tentang bagaimana keberagaman kultural diakui bermasalah karena diandaikan penyebabnya berasal dari cara pandang yang salah dan hanya karena cara pandang yang salah.Biasanya penjelasannya diteruskan dengan pandangan bahwa cara pandang yang salah ini bersumber dari kesalahpahaman memahami teks-teks sakral, baik tradisi maupun kitab suci. Maka, solusinya adalah dekonstruksi!
Lihatlah, sejak itu, metode paling dominan di sekolah ilmu-ilmu sosial dan agama adalah dekonstruksi. Anak-anak IAIN/UIN yang berlatar belakang santri diperkenalkan dengan teori-teori kritik wacana untuk mendekonstruksi makna-makna yang tersembunyi di balik teks kitab suci–dan mereka tampak dibuat terpesona.
Demikian pula anak-anak FISIP dan sastra atau ilmu budaya. Pokoknya bagi generasi yang kuliah sejak 1980-an dan setelahnya, solusi untuk mengatasi masalah keberagaman kultural adalah dengan mendekonstruksi teks yang selama ini mereka percayai sepenuh hati. Arus intelektual yang mengagung-agungkan keberagaman kultural ini seakan-akan mendapatkan pembenarannya setelah munculnya berbagai aksi radikalisme dan terorisme.
“Tuh kan benar?”, kurang lebih demikian komentar orang-orang yang telah terhipnotis kata-kata keberagaman kultural itu.
“Cara pandang mereka salah! Wawasan mereka sempit! cakrawala pemikiran mereka terbatas!”, mereka bersungut-sungut menunjuk kalangan yang secara simbolis memang suka mengenakan atribut keagamaan berlebihan itu.
Akan tetapi, karena terfokus hanya pada keberagaman kultural, para aktivis sosial dan pemangku kebijakan tidak lagi atau kurang melihat adanya ketimpangan sosial.
Bahkan ketimpangan sosial dianggap bagian dari keberagaman kultural yang harus diakui–maksudnya diterima sebagai sunatullah! Jika pun dianggap masalah, ketimpangan sosial dipahami sebagai masalah pribadi yang mesti diatasi dengan cara meningkatkan kompetensi–meritrokrasi.
Maka, sekolahlah tinggi-tinggi, tambah skill, dan perluas jaringan agar bisa berkompetisi di pasaran kerja nanti! Arahan-arahan untuk sekolah tinggi-tinggi, tambah skill, dan perluas jaringan tentu saja penting dan berguna bagi kelas menengah dan kaum elite. Mereka memiliki titik pijak yang kuat, keluarga yang mapan, serta lingkungan yang mendukung.
Apakah arahan-arahan tersebut bisa berlaku bagi anak-anak dari kelas bawah, masyarakat umumnya?
Singkatnya, di balik kata-kata keberagaman kultural terdapat kompleksitas masalah ketimpangan sosial yang sedemikian rupa sehingga tertutupi. Inilah yang sering saya sebut sebagi proses neoliberalisasi.
Banyak orang tidak menyadarinya, termasuk para akademisi. Masalahnya tidak hanya apakah kata-kata keberagaman kultural secara etis adalah baik atau buruk, tetapi juga dan terutama efek samping yang ditimbulkannya belum atau tidak disadari. Seolah-olah ini adalah hal normal, padahal bukan.
Demikian.